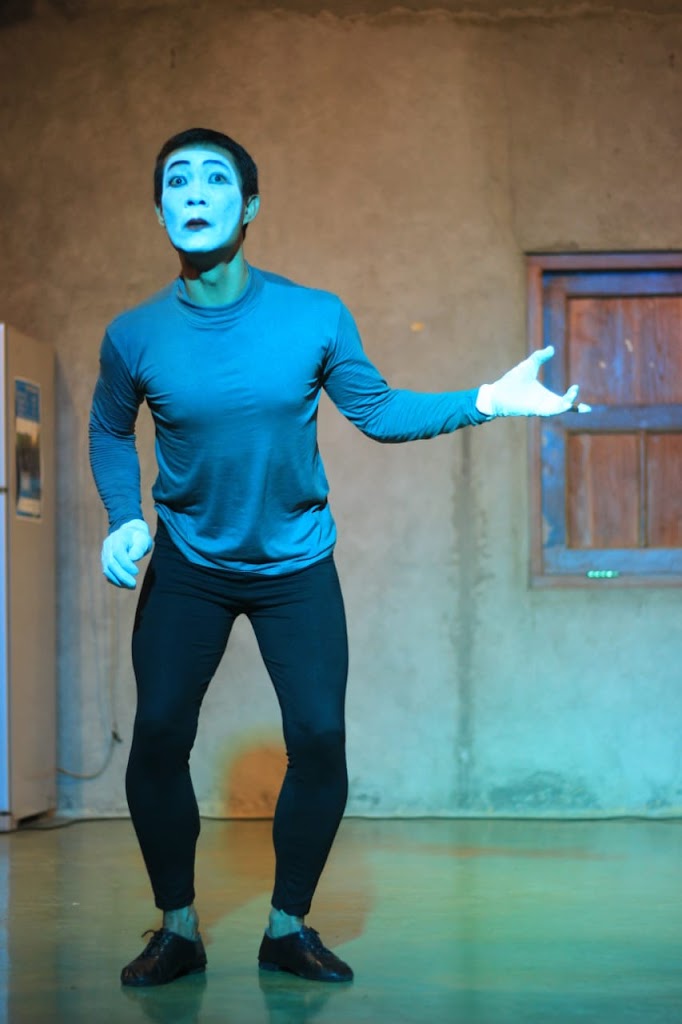Minggu, 26 Mei 2019 | teraSeni.com~ Pada Rabu, 2 Mei 2019, Gerobak Kopi, sebuah kedai kopi yang berada di jalan…
Kategori: Uncategorized
Tengok Bustaman IV; Bustaman Untuk Dunia Mengulas Figur Kai Bustam Lewat Galeri Kampung
Rabu, 8 mei 2019 | teraSeni.com~ Semarang—Aroma khas kambing menyeruak memenuhi udara. Dari ujung gang, sampai jalan- jalan sempit, memperlihatkan…
Para Pensiunan 2049 : Balada Koruptor yang Dikejar hingga Alam Kubur
Rabu, 24 April 2019 | teraSeni.com~ Seonggok jenazah lelaki paruh baya tidak bisa disemayamkan. Sang penjaga kubur kekeh menolak untuk…
Sesaji Nagari: Mewacanakan Persatuan Melalui Musik
Minggu, 7 April 2019 | teraSeni.com~ Ketika musik-musik etnik yang sudah familier di telinga masyarakat awam terus direproduksi; ketika banyak…
Dibalik Pembatalan Konser Slank Di Aceh
Selasa, 22 Januari 2019 | teraSeni.com~ Slank adalah grup band rock asal Jakarta yang kariernya terbilang gemilang dan konstan di…
Nosheheorit: Dialog Gender dalam Proses Menjadi Lengger
Jumat, 28 Desember 2018 | teraSeni.com~ Seorang laki-laki menggunakan kemban merah meratap dengan wajah nanar ke penonton. Di dalam pelukannya,…
Teriakan Sunyi Milenia*
Kamis, 13 Desember 2018 | teraSeni.com~ Mime on Stage serta Temu Karya Mimer meningkahi geliat milenia dengan pantomim. Kesunyian yang…
Pertemuan Komunitas Seni Anak Muda Sumatra Barat (Catatan Lokakarya: Kota dan Seni Anak Muda)
Minggu, 2 Desember 2018 | teraSeni.com~ Di pertengahan Oktober 2018 lalu, saya diajak bertemu oleh Roni “Keron” Putra di Padang.…
Musim Paceklik Ngayogjazz
Rabu, 28 November 2018 | teraSeni.com~ Keramaian adalah hal yang lumrah untuk Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul Yogyakarta. Pasalnya di desa…
Hubungan Pecah Semudah Pecah Belah
Selasa, 23 Oktober 2018 | teraSeni.com~ Seorang penari berdiri tegap di atas 35 tumpukan piring dengan tangan terbentang. Ibu jarinya…