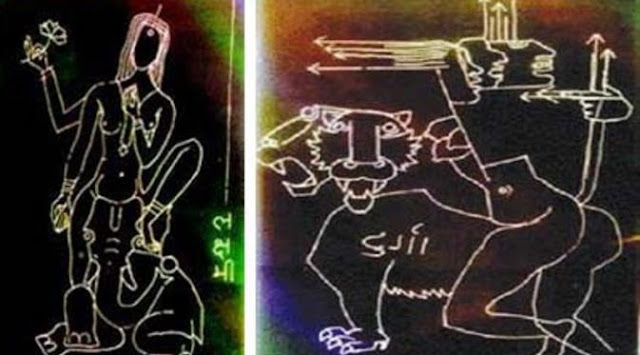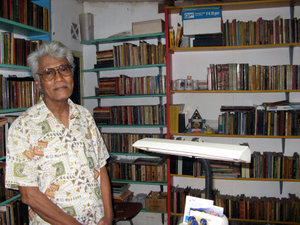“
One of a critic’s main jobs is to prick balloons.”(Eric Bentley)
Satu
Menulis kritik teater, kata Eric Bentley (1958: 235) adalah lebih buruk ketimbang jalan di atas telur; rasanya seperti kita jalan di atas tubuh-tubuh manusia yang hidup dan menyebabkan tubuh-tubuh itu berdarah-darah. Dan barangkali agak berlebihan bila ia menambahkan, bahwa ia merasa kritik teater itu merupakan seni membuat musuh dan gagal mempengaruhi orang. Namun orang ini terus juga menulis kritik-kritik teaternya sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan yang ia miliki tentang kritik.
Umpamakan tak ada kritik teater yang serius; maka pujian-pujian dari apa yang “sok disebut kritikus” itu juga tidak akan diterima dengan serius. Bila semua lakon dan semua pementasan dipuji, sebuah kritik teater yang baik tidaklah akan berarti apa-apa. Seniman yang dikritik belajar memfokuskan diri pada kritik-kritik yang menyalahkan dia dan melupakan yang lain; sebagian besar mereka bersikap seperti itu. Mereka yang tak tahan (terhadap kritik) biasanya bukanlah mereka yang lapar akan sedikit pengakuan, tetapi mereka yang telah kenyang dengan pujian yang berlimpahan. Kebudayaan kita sudah terlalu banyak menjual setiap produk Reputasi-reputasi tidaklah selalu benar-benar tinggi, mereka malah terlalu banyak dipompa, sesuatu yang sia-sia.
Namun demikian, kita akan serempak berseru: kritik teater sangat diperlukan. Maju-tidaknya kehidupan herteater tergantung pada kritik-kritik teater yang berbobot. Kita seakan-akan merindukan kritik teater yang berbohot, kritik teater yang mencerminkan kecerdasan dan intelektualitas.
Dua
Ada kontroversi seputar masalah kritik sastra, termasuk kritik teater; persaingan antara sastrawan kreatif dan para kritikus dan ini adalah ceritera lama. Pertama, kita masih ingat metode kritik Ganzheit (Arief Budiman dan Gunawan Mohamad) yang mengingatkan kita pada ucapan Jean-Paul Sartre: “Karya sastra tidak bisa direduksi menjadi sebuah pemikiran” dan kritik akademik yang berpegang pada analisa, yang diwakili para sarjana sastra UI Rawamangun, yang mengingatkan kita pada The New School of Criticism. Dan debat ini telah dipecahkan melalui teori lingkaran, di mana diandaikan bahagian dan keseluruhan akan selalu mengandaikan secara terus-menerus dalam suatu lingkaran yang memutar.
Kedua, ada pertentangan antara otonomi pengarang dan otonomi semantic, atau antara textual meaning dan authorial meaning. Tugas teori dan metode adalah membantu kita memahami sifat-sifat objek sedekat mungkin dan bukan malah melakukan distorsi dengan menjadikan objek kajiannya hanya sebagai ilustrasi untuk suatu teori. (Ignas Kleden, 2004: 193). Kritik dinilai berdasarkan keberhasilannya atau kegagalannya dan bukan berdasarkan pendekatan yang digunakan.
Ketiga, antara pendapat yang mengatakan, bahwa semua lakon itu adalah baik dan pendapat yang mengatakan ada lakon yang baik dan ada yang tidak baik (dan menelurkan kriteria tentang lakon yang baik).
Naskah-naskah yang dibuat sendiri dipandang berbeda dengan naskah-naskah terjemahan dari luar negeri. Naskah-naskah buatan sendiri cenderung dipandang “kurang” memenuhi kriteria lakon yang baik. Seperti Peter Brook, umpamanya (1989: 46) memberikan kriteria umum tentang lakon yang baik dan yang tidak baik. Lalu ia menyimpulkan, masalah utama teater dewasa ini adalah: “How can we make plays dense in experiences?!“
George Lukacs rnenyebutnya sebagai “dilema intelektual kesusastraan”: sejauh mana sebuah lakon itu mampu melukiskan keadaan suatu masyarakat sambil mengusulkan suatu dunia baru, suatu possible word suatu proposed world. Sekalipun belum ada dalam kenyataan, sanggup mengundang dan meyakinkan penonton tentang perlunya dunia tersebut; suatu masa depan yang hakiki, masa depan sebagai suatu “struktur konseptual” suatu penganganan dramatik. Brook lagi: jika suatu lakon itu mengkonfirmasikan pada kita sesuatu yang sudah kita yakini atau percaya, maka lakon itu tak ada gunanya. Kecuali, tentu saja lakon itu mengkonfirmasikan the real belief, di mana teater dapat membantu kita untuk melihat dan memahami dengan lebih baik.
Tiga
Ada tiga persoalan yang mendasar dalam usaha kita membuat kritik teater yang baik pertama, penganalisaan lakon lewat suatu studi terhadap naskah tersebut. Juga studi tentang latar belakang pengarangnya studi tentang fakta-fakta yang dominan pada periode tersebut –agama atau hal-hal yang bersifat psikologis-dan sejauh mana naskah itu (bisa) dieksekusi ke dalam realitas pentas. Kedua, kemungkinan-kemungkinan teatral dari naskah tersebut yang meliputi kebutuhan visual, kebutuhan verbal, kebutuhan karakteristik dan kontak antar karakter, kebutuhan struktural serta kebutuhan auditif-kontras, jedah yang baik dan ilustrasi musik. Ketiga, menunjukkan kriteria yang digunakan dalam penilaian.
Menurut Max Lerner pengarang mempunyai dua macam filsafat: kredo artistik yang sadar lewat medium drama dan visinya tentang kehidupan serta nilai yang terletak di bawah sadarnya—pandangan hidupnya berupa pengendapan fakta-fakta yang datang dari luar. Sernentara tujuan dan kritik teater, Oscar G.Brockett (1964: 19) menyebut tiga tujuan: expository, appreciation dan evaluative. Mungkin saja dalam sebuah kritik teater ketiga tujuan tersebut terdapat bersama-sama. Kritik teater expository antara lain mempelajari pengarangnya, kapan naskah itu ditulis, sumber-sumber dan ide-ide yang diekspresikan dalam naskah.
Kritik teater yang apresiatif biasanya ditulis oleh kritikus teater yang telah memutuskan, bahwa naskah tersebut adalah baik. Motif utamanya adalah agar orang lain, masyarakat penonton juga ikut merasakan kekuatan naskah tersebut. Bisa juga kritikus tersebut menguraikan responnya sendiri kemudian membangkitkan perasaan yang sama pada pembaca penonton. Atau bisa juga ia memperlihatkan kesungguhan penulisnya dalarn struktur naskah, karakterisasi, penciptaan mood, dan lain- lain. Kritik teater yang evaluative bisa menggunakan (kritik) expository, appreciative dan bahkan bisa menghukumnya. Tujuan utamanya adalah menilai efektivitas dari naskah tersebut.
Dengan demikian kita mendapat bayangan kira-kira bagaimana seorang kritikus teater yang “baik” itu, yaitu: (1) Ia harus sensitive terhadap perasaan dan ide-idenya; (2) Ia harus mengenal benar teater dari segala periode dan semua tipe/gaya/aliran, terutama perkembangan teater di Indonesia sehingga tampak tahap-tahap hubungan dialektik antara teater setempat dan pengaruh-pengaruh dari luar terutama yang merangsang bangkitnya kesadaran kecendikiawanan perteateran (Bakdi Soemanto, 2001: 120); (3) Ia harus mau mengeksplore naskah lakon sampai ia memahaminya secara tuntas; (4) Ia harus awas, hati-hati terhadap prasangka pribadi dan nilai-nilainya; (5) Ia harus pandai berbicara dan jelas dalam mengeluarkan penilaiannya dan dasar-dasarnya; dan (6) Ia harus mau mengubah pendapatnya bila ada pengalaman dan bukti-bukti baru.
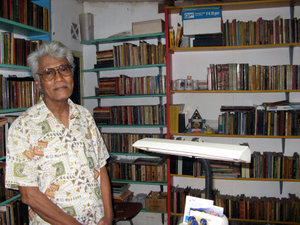 |
Almarhum Max Arifin
di Perpustakaan Pribadinya |
Peter Brook (1990: 37) menekankan, bahwa ia, kritikus teater itu mempunyai suatu citra (image) tentang bagaimana seharusnya sebuah teater itu berada dalam komunitasnya. Akan jauh lebih baik bila ia menjadi orang dalam (insider). Ia menceburkan diri ke dalam hidup kita,bertemu dengan para aktor, berbicara dan berdiskusi, menyaksikan dan (kalau perlu) campur tangan. Memang terdapat sedikit masalah: bagaimana mungkin seorang kritikus berbicara pada seseorang yang tadinya dikecam dalam surat kabar. Bagaimanapun juga hubungan itu tetap dijaga dan diperbaiki karena keduanya saling membutuhkan. Kritikus yang tidak lagi menyukai teater adalah “a deadly critic”; kritikus yang mencintai teater tetapi tidak dengan tegas dan jelas apa yang dimaksudkan dalam kritiknya, juga adalah “a deadly critic”.
Kritikus yang baik adalah kritikus yang dengan jelas memformulasikan untuk dirinya sendiri (lebih dulu) bagaimana seharusnya sebuah teater dan cukup berani melemparkan formula tersebut ke dalam “kancah yang beresiko” setiap waktu, saat ia berpartisipasi dalam peristiwa teater. Memang berat baginya untuk mempertahankan suatu antusiasme bila cuma ada sedikit lakon yang baik: suatu pilihan yang tidak menyenangkan antara karya-karya besar konvensional dan karya-karya modern yang kurang baik. Brook menulis di sana: “We are now in another area of the problem, also considered to be central: the dilemma of the deadly writer”. Apakah pernyataan ini berlaku juga bagi kita di Indonesia? Ada kecenderungan lakon-lakon itu cumalah pengulangan atau penulisan dalam bentuk baru. Drama lalu menjadi kantong pakaian-pakaian rombeng, keisengan dan ide- ide yang kemarin.
Menurut Eric Bentley, kemunduran ini disebabkan oleh dua hal: (1), penulisan naskah lakon cuma dipandang sebagai suatu craft, ketukangan. Dramaturgi diturunkan dan the fine arts menjadi the useflul arts dan juga tidak berguna:, (2). Naskah ditulis khusus untuk penonton tertentu yang ada dalam pikirannya dan tidak berpikir ada penonton yang lain untuk naskah yang baik. Alasan utamanya adalah untuk menarik perhatian dan menyenangkan penonton. Dia melihat dramaturgi itu sebagai persoalan bagaimana menepatkan lakon itu pada penontonnya; yang benar adalah penonton itu diminta/dihimbau to adjust dirinya pada lakon tersebut.
Empat
“Is there another language just as exacting for the author as a language of words?,” tanya Brook lagi ketika ia berbicara tentang The Holy Theatre sebagai suatu penghormatan bagi Artaud. (hal.55). Apakah ada bahasa untuk actions, untuk suara, “a language of word-as-part-of movement”, “of word-as-lie, word-as-parody, word-as-rubbish, word-as-contradiction, word-shock or word cry”? Teater yang mencoba memberikan arti yang lebih dalam lagi tentang gestur, umpamanya; gestur sebagai suatu statement, ekspresi, komunikasi dan suatu manifestasi pribadi tentang kesepian, yang disebut Artaud sebagai “a signal through the flames” sekaligus sebagai tempat berbagi pengalaman begitu kontak itu terjadi. Perlahan-lahan kita menuju ke “wordless language” yang lain: kita mengambil sebuah peristiwa, sepotong pengalaman dan membuat gerak-gerak dengan tubuh yang mengubahnya menjadi bentuk-bentuk di mana kita dapat saling berbagi.
Kita mendorong para aktor itu untuk melihat diri mereka bukan hanya sebagai improvisers, menuntun diri mereka ke dalam inner impulses mereka, tetapi sebagai seniman bertanggung jawab mencari dan menyeleksi di antara bentuk-bentuk tersebut sehingga sebuah gestur itu atau sebuah teriakan menjadi sebuah objek yang ia temukan dan bahkan dibentuk-ulang. Kita menolak bahasa topeng tradisional dan dandanan-dandanan sebagai sesuatu yang tidak cocok lagi. Kita bereksperimen dengan keheningan kita ingin menemukan hubungan antara keheningan dengan durasi. Kita bereksperimen dengan ritual dalam arti pola-pola yang berulang-ulang, melihat apakah hal itu mungkin untuk menghadirkan lebih banyak arti lagi dan lebih cepat ketimbang lewat suatu pembongkaran peristiwa secara logik. Tujuannya, seperti dikatakan oleh Brook, adalah bagaimana yang tidak tampak itu menjadi tampak lewat kehadiran para aktor, terlepas buruk atau baik atau sukses atau gagal.
Seperti dikatakan sendiri oleh Artaud (Stephen Barber, 1993: 44) teaternya tidak mempercayai lagi bahasa, karena teks itu cumalah pengulangan-pengulangan yang nyinyir. Di bagian lain Artaud menulis begini (hal. 145):” the theatre is the condition the place the point where the human anatomy can be seized and used to heal and direct life.” Persoalannya bagi kita atau bagi (calon) kritikus teater: rasanya kita belum mempunyai rumusan atau kriteria yang baku dalam menilai pementasan-pementasan yang mengambil gaya Artaudian. Apakah hal itu perlu atau tidak perlu dirumuskan seperti yang terjadi pada teater-teater yang mengambil gaya Brechtian atau Chekhovian. Kriteria tersebut juga diperlukan oleh para penonton agar mereka mengetahui bagaimana kita menikmati pergelaran-pergelaran Artaudian tersebut.
Lima
Perlukah para kritikus mempunyai sebuah organisasi? Saya tidak bisa menjawab secara tegas. Di lnggris ada Guild of Drama Adjudicators atas restu dari British Drama League. Pada awal pembentukannya organisasi ini beranggotakan empat puluh enam orang, orang-orang yang mempunyai pengalaman yang baik dalam festival-festival drama. Sekarang anggotanya sebanyak dua ratus lima puluh orang dengan cabang-cabangnya di New Zealand, Kanada, Australia dan Amenika Serikat. Organisasi ini membuat standar penilaian terhadap pementasan-pementasan. Syarat-syarat keanggotaannya cukup ketat. Anggota-anggotanya adalah orang-orang professional, berpengalaman sebagai aktor, sutradara, stage manager atau produsir. (Derek Bowskill, 1973: 328). Di Inggris juga ada British Theatre Association, The National Association of Drama Advisers ada pula National Drama Conference, National Federation of Women’s Institutes, The National Operatic and Dramatic Association. Mereka mempunyai program kerja yang luas: pelatihan-pelatihan, effective speech courses, pelayanan perpustakaan, informasi, penerbitan bulletin, pelatihan menjadi kritikus, penulisan naskah, ceramah-ceramah, konsultasi, dan lain-lain.
Apakah tidak mungkin kita memikirkan organisasi-organisasi seperti di lnggris itu ? Saya mendukung gagasan untuk membentuk Federasi Teater Indonesia.
Di samping itu perlu dipertimbangkan agar PT-PT Seni dan sanggar-sanggar mampu memunculkan kritikus-kritikus teater yang handal seperti dirisaukan oleh Bakdi Soemanto dalam bukunya Jagat Teater (2001: 321). Ia juga mengkritik sutradara beberapa sanggar yang bertindak sebagai pemilik dari company itu yang tidak memungkinkan munculnya kritikus-kritikus teater dari sana.
Enam
Sesungguhnya teater itu berada dalam situasi antara kekuatan-kekuatan yang sedang bertanding yang memberinya hidup; teater itu sendiri adalah pemberi hidup. Kita ingat akan The Great Initiatory Wheel-nya Richard Schechner (1994: 318) yang terbentuk bila kerja kelompok itu sukses. Personal (yang mempertanyakan siapa aku sekarang) sebagai suatu realisasi diri menuju ke Group (munculnya kreativitas kolektif)… .menuju ke social (solidaritas)… .menuju ke Political (kesadaran)… menuju ke Metaphysical (manusia dapat mengubah dirinya)… menuju kembali ke Personal dan seterusnya dalam sebuah lingkaran yang makin menaik
Ya, bagaimana lagi? That’s all. Terima kasih. Casa di Lansia, 20 Juni 2005.(Max Arifin)