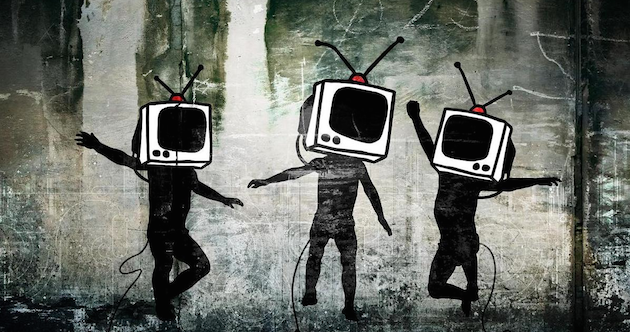oleh teraseni | Agu 6, 2016 | Uncategorized
Sabtu, 6 Agustus 2016 | teraSeni ~
Televisi dengan kekuatan teknologi yang dimilikinya dianggap oleh banyak kalangan sebagai penanda kehidupan modern. Betapa tidak, masyarakat masakini seperti tidak dapat dipisahkan dari televisi. Keduanya bahkan ibarat simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan di antara kedua belah pihak. Televisi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, yang berfungsi selain sebagai penyebar informasi dan hiburan, juga sebagai alat propaganda yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang dengan membuatnya percaya dan yakin terhadap pesan yang ada dibalik tayangan televisi itu.
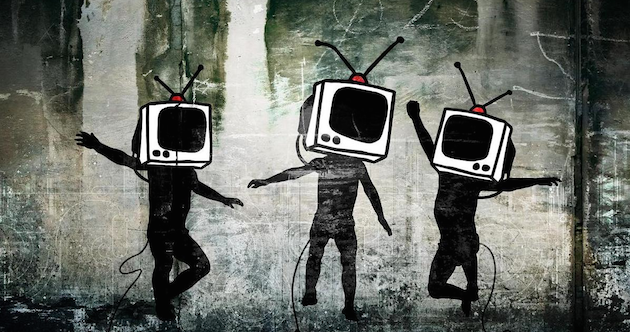 |
Ilustrasi tentang propaganda di televisi
(sumber:www.wakingtimes.com) |
Kekuatan utama televisi adalah gambar, dan apapun gambar yang ditayangkannya bisa berdampak pada perilaku orang yang melihatnya. Menyadari kekuatan inilah banyak politisi memanfaatkan media televise sebagai sarana propaganda bagi kepentingan politiknya. Berbagai macam cara perekayasaan gambar dilakukan demi tercapainya tujuan yang diharapkan. Manipulasi gambar tayangan televisi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mempengaruhi pemirsa, agar percaya dan yakin dengan pencitraan dari tayangan tersebut.
Padahal, semua gambar tayangan televisi bukanlah gambar yang sebenarnya, melainkan sudah mengalami penyuntingan atau pengeditan sesuai dengan strategi yang telah direncanakan. Sayangnya, hanya sedikit dari pemirsa yang tahu dan memikirkan hal itu. Hal inilah yang tak terbayangkan oleh kita, bahwa dibalik tayangan yang spektakuler itu, terselip maksud ‘busuk’ yang berusaha mempengaruhi perasaan dan kesadaran kita. Diperlukan suatu kekuatan dan kejernihan berpikir dalam mencerna segala tayangan, agar tidak terjerumus dengan sarana propaganda melalui tayangan televisi.
Hal yang menarik dewasa ini ialah ketika kegiatan seni dimanfaatkan oleh para politikus untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, sebagai senjata untuk memenangkan pemilu. Padahal, di luar itu mereka tidak peduli pada kegiatan seni. Salah satu contohnya ialah apa yang dilakukan oleh presiden kita saat, Jokowi, ketika ia memanfaatkan media televisi dan seni pada pemilu dua tahun lalu. Ya, Jokowi adalah contoh paling jelas, dari bagaimana seni dan televisi digunakan untuk mendapatkan simpati. Dengan memanfaatkan jasa band terkenal seperti Slank, yang terkenal dengan lagu-lagunya yang berisikan pesan perjuangan membela Indonesia, Jokowi berhasil menarik simpati masyarakat, terutama anak muda. Setidaknya, hal ini telah membuat para Slankers memilih Jokowi.
Pencitraan yang didapatkan oleh para politikus dari media televisi ini sungguh hebat. Semua yang tergambar pada setiap frame menjelaskan kebaikan, kedermawanan, kehebatan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para politikus. Jarang sekali ada tayangan yang memperlihatkan sisi buruk dari mereka. Tidak saja media televisi yang dimanfaatkan, beberapa media cetak yang siap terbit setiap harinya juga dipenuhi ‘koar-koar’ janji para politikus untuk membangun pencitraannya. Masyarakat diajak menilai sesuatu berdasarkan pencitraan yang tidak nyata ini. Mendadak, seni lalu diagung-agungkan, misalnya dengan mengangkat kembali kesenian tradisi sebagai visi misi dalam kampanye. Berbagai macam pertunjukan seni diadakan di desa-desa yang didanai oleh para politikus dengan embel-embel baliho yang terpajang di sepanjang jalan.
Apakah seni masih pantas dianggap sebagai suatu keindahan ketika ia hanya dimanfaatkan sebagai sarana pencitraan? Pada umumnya, seni diartikan sebagai wahana keindahan, perbuatan manusia yang timbul dari perasaan, sehingga menggerakan jiwa dan perasaan manusia lain. Seni adalah suatu kreativitas yang diciptakan oleh manusia yang berasal dari ide, gagasan, perasaan, suara hati, gejolak jiwa, yang diwujudkan atau di ekspresikan. Dari pengertian seni ini seharusnya seni benar-benar dijadikan sebagai wahana kebudayaan untuk menciptakan keindahan dan hiburan, bukan untuk mendapatkan pencitraan demi mendapatkan jabatan.
Banyak juga orang yang demi mengejar ambisi tertentu, lantas mengemas dirinya terlalu berlebihan. Mereka berupaya mengekspos diri dengan berbagai cara. Dengan adanya sosial media, orang kini bahkan bisa bebas menciptakan citra diri untuk mencapai tujuan tertentu. Orang seperti ini ‘berbahaya’, karena akan tumbuh menjadi ‘narsis’ yang bisa menghalalkan segala cara untuk meraih ambisinya.
Seni dalam pencitraan adalah seni yang tidak berbicara apa adanya. Mendengarkan atau menonton kegiatan seni dalam iklan atau pidato kampanye diwarnai ambiguitas atau ketidakpastian. Ini disebabkan oleh pencitraan yang terlalu berlebihan. Lebih dari 63 persen caleg, menurut KPU Pusat, tidak memiliki pekerjaan yang jelas. Itu artinya, ada tindak improvisasi ‘kotor’ dalam penggunaan seni sebagai sarana pencitraan, padahal improvisasi adalah bayi yang dilahirkan oleh dunia kesenian. Pada situasi politis demikian, kita dihantui kecemasan, karena seni akan semakin berkurang maknanya, terlebih jika di dalamnya terdapat pencitraan yang berlebihan.
Tetapi kenapa seni justru dilarang untuk jadi ajang kreatifitas dan medium kritik? Pertanyaan ini saya ajukan karena ketidakseimbangan antara seniman dengan politikus? Jika seseorang pejabat dapat melakukan pencitraan dengan seni, lalu kenapa seniman tidak diperbolehkan untuk menyampaikan kritik melalui seni? Kita ingat bahwa musisi semacam Iwan Fals dan Sawung Jabo pernah dicekal masuk layar televisi, karena syair-syair lagunya yang dianggap membahayakan stabilitas pemerintahan (rezim Soeharto).
Demikian juga sastrawan WS Rendra yang pernah dilarang masuk televisi terutama untuk pembacaan puisi, karena karya-karyanya dianggap membahayakan kedudukan pemerintahan di mata masyarakat. Aktifitas Rendra pada masa itu seringkali mendapat kontrol ketat dari Departemen Penerangan, Kepolisian, bahkan Kodim. Ketika WS Rendra bergabung dengan group musik Swami, Rendra dan kelompok inipun dilarang tampil di televisi.
Jika siapa saja bebasmelakukan kegiatan seni, bebas mengekspresikan apa saja untuk dirinya dan penonton, kenapa banyak seniman yang dicekal? Seniman juga melakukan pencitraan dengan karyanya. Mereka ingin proses kreatif dari usahanya membangun kesadaran masyarakat dan mampu menjelaskan permasalahan negara saat ini, seperti lagu yang dibawakan Iwan Fals dan puisi WS Rendra.
Apa sebenarnya seni itu ketika dijadikan sebagai sekadar bagian dari pencitraan? Sungguh jelas bahwa pada abad 20 ini seni sangat dibutuhkan oleh semua kalangan. Para politikus memanfaatkan seni untuk pencitraan dan berbagai stasiun televisi memanfaatkan seni sebagai sumber uang. Seni dikembangkan sedemikian meriah sehingga seringkali melupakan hakikatnya sebagai wahana pengalman keindahan. Seni dimanfaatkan dengan menghadirkannya berbagai hiburan yang dipertontonkan tanpa keindahan.
Dr Nigel dalam filmnya yang berjudul “More Human Than Human” menunjukkan bagaimana pencitraan berhubungan erat dengan gambar, simbol, dan seni. Ia menjelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan ini terdapat ribuan tahun yang lalu, ketika nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu mewariskan seni di dalam bentuk visual. Bagaimana seniman pertama memperjuangkan peradaban terbesar. Ia menjelaskan hasil surveinya bagaimana manusia membentuk seni dan seni membuat kita menjadi manusia. Lalu bagaimana seni membentuk dunia?
Tidak ada yang mendominasi hidup manusia begitu besar. Namun bentuk tubuh manusia menjadi obsesi beberapa seniman besar dunia. Faktanya, citra bentuk tubuh manusia tidak satupun mirip dengan bentuk manusia pada nyatanya. Mereka jarang mencipta tubuh yang realistis. Jika diperhatikan, kelima seri film Dr Nigel menjelaskan secara rinci awal mula seni sebagai pencitraan, dan bagimana perkembangan seni yang ternyata telah dimafaatkan oleh banyak orang dari dahulu hingga sekarang.
Filsafat seni bersangkutan dengan masalah-masalah konseptual yang muncul dari pengertian kita tentang seni. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seperti pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Nigel dalam film-filmnya merupakan bagian dari pertanyaan dasar dalam estetika atau filsafat seni, yaitu: Bagaimana awal mulanya seni? Bagaimana seni di definisikan? Apa yang membuat karya seni indah, menarik dan jelek? Bagaimana seseorang menanggapi karya seni? Apakah ungkapan artistik merupakan bentuk ungkapan yang unik? Apakah seni menyingkap kebenaran tentang segala sesuatu? Mengapa manusia menciptakan karya-karya seni?
Pada umumnya seni adalah segala melalui unsur-unsur tertentu, yang bersifat indah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tak terbatas. Seni dapat mengharukan, seni dapat menyatukan seluruh kalangan maupun komunitas, seni juga dapat menciptakan keakraban dapat menciptakan hal-hal lain yang tidak dapat kita bayangkan. Seni adalah kegiatan yang menghasilkan karya indah. Tujuan seseorang berkesenian di antaranya untuk kepuasan pribadi, tuntutan keadaan, tujuan praktis untuk mencari uang, dan ada pula demi kepentingan kesejahteraan umat manusia.
Intinya, seni pada dasarnya adalah kegiatan untuk menghibur. Tapi jika seni terus dimanfaatkan sebagai sarana pencitraan yang berlebihan untuk mendapatkan simpati dari banyak orang, sei akan berkurang maknyanya.Seorang menciptakan karya seni dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan zamannya sehingga memilki arti penting bagi generasi berikutnya, tapi seni untuk pencitraan diciptakan untuk menghipnotis pikiran masyarakat untuk melihat seseorang secara berlebihan. Demikian pula pandangan masyarakat yang ‘meminggirkan’ seni dalam proses pendidikan maupun kehidupan sehari-hari seharusnya telah ditinggalkan. Sebab, tujuan manusia menciptakan karya seni adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan zamannya, dan bukan merusaknya.
oleh teraseni | Agu 2, 2016 | Uncategorized
Selasa, 2 Agustus 2016 | teraSeni ~
 |
Salah satu penampilan tari Pasambahan
dalam acara Masakini
(Sumber: www.tradisikita.my.id) |
Tujuh orang laki-laki berpakaian tradisional daerah Minangkabau secara rampak memperagakan gerakan-gerakan mancak (pencak), semacam variasi gerak silek (silat) yang diakhiri dengan sambah (sembah) hormat kepada para tamu. Setelah mereka tujuh orang perempuan, berpakaian adat lengkap menggunakan suntiang (sunting) dan memegang carano (cerana), sementara enam lainnya mengenakan tikuluak tanduak (kain berbentuk tanduk), menarikan gerak-gerak yang kebanyakan berakhir dengan gerak sambah dengan kedua tangan dirapatkan di depan dada.
Diiringi suara bansi (alat tiup tradisional), perempuan yang mengenakan suntiang ditemani dua orang yang mengenakan tikuluak tanduak dan salah seorang laki-laki yang tadi mempergakan mancak kemudian berjalan pelan dan anggun ke arah para tamu. Sesampai di hadapan para tamu, mereka berempat membungkukkan badan, sang laki-laki membukakan tutup carano dan mempersilahkan beberapa orang tamu untuk mengambil sirih dan pinang. Sementara itu, terdengar suara seperti deklamasi dalam bahasa Minangkabau dari pengeras suara mengiringi mereka.
Adegan di atas bukanlah upacara adat atau alek (helat) pengangkatan pangulu (pemuka adat) di Minangkabau, melainkan adalah pemandangan dalam sebuah pembukaan acara bertajuk Malam Pagelaran Kesenian Minangkabau, Dies Natalis ke-36, Unit Kesenian Minangkabau (UKM) ITB, yang digelar di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB, Bandung, Jumat 22 April 2011. Tari yang dalam tayangannya di situs youtube diberi judul “Tari Galombang Pasambahan (Dies Natalis 36) UKM-ITB” itu mengawali acara yang mengusung tema “Minangkabau for Indonesia,” yang menurut rilis panitianya dihadiri sekitar 900 orang penonton yang membeli tiket.
Pemberian judul ‘Tari Galombang Pasambahan’ tersebut di atas menarik karena menggabungkan dua nama tarian yang biasanya digunakan terpisah dalam khasanah seni tari Minangkabau, yakni Tari Galombang atau Tari Pasambahan. Semakin menarik, karena tarian itu tidak ditampilkan dalam suasana perhelatan adat-istiadat masyarakat Minangkabau, melainkan dalam suatu acara yang cenderung bernuansa kehidupan modern yakni sebuah Dies Natalis organisasi. Menarik pula untuk mencermati bahwa penampilan tari Galombang atau tari Pasambahan tersebut berlangsung di rantau, atau jauh dari kampung halaman, oleh sebuah organisasi mahasiswa asal Minangkabau. Sementara, ada pernyataan tentang tari Galombang, yang mengatakan bahwa tarian ini lazimnya hanya ditampilkan sebagai bagian upacara adat di Minangkabau, terutama untuk pengangkatan pangulu.
Budaya Populer dan Tari Pasambahan
Seperti berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat juga terlibat secara aktif dalam gegap gempita budaya pop. Kata ‘pop’ menurut Raymond William secara diskursif berasal dari kata ‘populer,’ yang mempunyai makna: disukai banyak orang dan memang diciptakan untuk menyenangkan banyak orang. Adapun menurut Dominic Strinati, budaya populer dihasilkan secara massal dengan bantuan teknologi industri, dan dipasarkan secara professional bagi publik konsumen dengan tujuan untuk mendatangkan profit.
Menurut Dominic Strinati, budaya populer atau budaya massa berkembang, terutama sejak dasawarsa 1920-an dan 1930-an, yang ditandai dengan munculnya sinema dan radio, produksi massal dan konsumsi kebudayaan yang terjadi karena adanya kemajuan media dan teknologi. Budaya pop menghilangkan batasan antara budaya tinggi dengan budaya rendah dan kerap kali dihubungkan dengan ciri-ciri kehidupan postmodernisme.
Memang ada pengaruh kecil dari hal-hal lain, namun identitas didominasi oleh pengaruh dari budaya populer. Budaya populer, menurut Heryanto, perlu dipahami sebagai pelbagai ’’…suara, gambar, dan pesan yang diproduksi secara massal dan komersial’’ dan juga ’’…berbagai bentuk praktik komunikasi lain yang bukan hasil industrialisasi, relatif independen, dan beredar dengan memanfaatkan berbagai forum dan peristiwa seperti acara keramaian publik, parade, dan festival’’ (hlm 22).
Karena itu, bisa dikatakan bahwa identitas Minangkabau populer tersebut juga terbentuk melalui film dan sinetron. Sebagai media komunikasi yang menggunakan audiovisual, pencitraaan tentang Minangkabau masakini dibangun. Namun yang paling kuat pengaruhnya adalah perkembangan internet, terutama melalui media social semacam Twitter, Facebook, dan instagram, yang berperan sebagai pasar citra dan teks.
Seperti halnya masyarakat di beragai daerah di Indonesia, mayoritas penduduk Sumatera Barat juga tergiur dan berperan aktif di dalam budaya populer. Hal itu misalnya tampak dalam berkembangnya industri rekaman lagu pop Minang sejak tahun 1980-an, juga melalui perkembangan Talempong kreasi atau talempong goyang dewasa ini.
Konsumsi budaya pop juga terjadi melalui campur tangan ‘organ tunggal’ yang sempat mewabah di Sumatera Barat. Tentu saja peranan televisi juga tidak kecil dalam menciptakan selera populer ini. Melalui berbagai acara, sejak zamannya TVRI, ‘tari kreasi’ Minangkabau ditampilkan dan diterima sebagai identitas tari secara bersama oleh masyarakat Minangkabau. Melalui penampilan di televisi pula, masyarakat Minangkabau yang berada di rantau terhubung dengan kampung halamannya.
Perkembangan itu diikuti pula oleh berkembangnya jenis tarian yang dinamakan sebagai ‘tari kreasi’ juga sejak dasawarsa 1980-an. Apa yang dinamakan sebagai ‘tari kreasi’ ini umumnya adalah jenis tarian yang dikembangkan dari berbagai tema-tema sehari-hari dengan memanfaatkan ragam gerak dari tari-tari tradisional. Sepintas, hal ini seperti melanjutkan cita-cita pengembangan tari Minangkabau modern yang diperjuangkan Huriah Adam dan Gusmiati Suid. Hal inilah yang dapat dilihat sebagai konteks dari perubahan tari Galombang menjadi tari Pasambahan.
Penampilan Tari Galombang Pasambahan dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-36, Unit Kesenian Minangkabau (UKM) ITB di atas karena itu dapat dilihat sebagai salah satu ciri dari berkembangnya budaya popular. Pada mulanya tari Pasambahan merupakan kesenian tari yang dinamakan tari Galombang, yang berasal dari Minangkabau. Tari Galombang dimaksudkan sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu. Setelah Tari Galombang, acara biasanya dilanjutkan dengan suguhan Daun Sirih dalam Carano kepada Sang tamu.
Jika ditelusuri, maka Tari Pasambahan semula diciptakan oleh Syofyani pada tahun 1962, yang ditampilkan untuk penyambutan Raja Belgia (Belanda) di Bukittinggi. Sebagaimana halnya di daerah lain, untuk menyambut para tamu yang datang ke daerah tersebut, disambut dengan suatu upacara adat yang dibuka dengan tarian penyambutan tamu. Itulah kiranya tari Pasambahan semula berkembang sebagai tarian untuk kegiatan penyambutan tamu.
Tari Pasambahan, yang kini terkadang juga disebut tari Galombang kreasi, menjadi salah satu tarian tradisional yang sangat populer di Sumatera Barat, khususnya di kota-kota. Tari ini sering ditampilkan pada acara-acara seremonial pembukaan acara resmi pemerintah dan acara resmi lainnya. Tarian tari Galombang kreasi atau tari Pasambahan telah dibuat lebih sederhana dari tari galombang yang asli. Durasinya pun cenderung lebih pendek. Galombang kreasi kini berkembang pesat, bagaikan menjamur di musim hujan, meliputi persebaran dan frekuensi pementasan, fungsi dan bentuk penyajiannya. Hampir semua wilayah perkotaan di Sumatera Barat kini mengenal tari Galombang kreasi ini.
Masyarakat di setiap wilayah bahkan seolah-olah berlomba-lomba menampilkannya. Hampir tidak ada resepsi besar yang berlalu tanpa kehadiran Galombang kreasi. Fungsinya pun turut berkembang beriringan dengan aspek-aspek yang lain. Kehadirannya selalu digunakan untuk penyambutan tamu, terutama dalam kemeriahan resepsi pernikahan. Tidak hanya untuk menyambut tamu dan memeriahkan resepsi pernikahan, tari ini juga disajikan untuk kepentingan pariwisata, menandai peresmian suatu bangunan, atau sebagai penanda pembukaan instansi tertentu. Bagi acara tertentu di kalangan pejabat pemerintah tari galombang selalu digunakan untuk menyambut camat hingga Presiden,
Berbeda dengan tari Galombang, koreografi tari Pasambahan sudah tertata secara profesional, sehingga dapat memberikan sajian estetis kepada tamu dan merupakan kebanggaan pula bagi yang punya acara jika dapat menjemput tari galombang untuk disajikan kepada tamunya. Semakin bervariasi koreografi tari galombang yang ditarikan dalam sebuah pesta, semakin tinggi pula kebanggaan atau “gengsi” seseorang atau semakin tinggi nilai penghormatan kepada tetamu. Ada pula yang berpendapat, kedua tari ini dapat dibedakan. Tari Galombang disajikan di luar ruangan, sedang tari Pasambahan untuk dalam ruangan. Wallahualam.
oleh teraseni | Jul 30, 2016 | Uncategorized
Sabtu, 30 Juli 2016 | teraSeni ~
 |
Salah satu produksi Waiting For Godot
(Menunggu Godot) Naskah Lakon
karya Samuel Beckett
(Sumber Foto:www.meanderite.com) |
Dilihat dari sejarahnya, seni pertunjukan sudah hidup selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Banyak jenis seni pertunjukan yang telah diselenggarakan, dipatenkan, dikembangkan dan menjadi suatu konvensi. Seni pertunjukan, dalam kancah kebudayaan dan kesenian, secara praksis tentunya memiliki banyak fungsi dan makna. Demikian pula, di baliknya terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh sang pengkarya.
Banyak bentuk kesenian selain seni pertunjukan, seperti seni rupa, desain komunikasi visual, film, dan lain-lain. Ada pula hal dipandang bukan seni namun mengandung unsur seni. Namun di dalam setiap karya seni terkandung nilai-nilai yang inheren, yang lazimnya dinamakan nilai estetika.
Kali ini kita akan melihat seni dan nilai estetika dalam suatu seni pertunjukan, lebih khususnya dalam seni teater. Secara ajeg, seni pertunjukan banyak membahas kehidupan, seperti agama, sosial, budaya, dan lainnya. Hal ini tentunya tergantung pada budaya dan semangat zaman yang sedang beringsut berkembang. Isu dan wacana menjadi senjata pamungkas sebagai pengaruh paling penting, khususnya dalam seni pertunjukan, meski hal ini juga terjadi pada seni-seni lainnya.
Seni pertunjukan tidak jarang ditujukan untuk mengajukan suatu argumentasi, yakni dari sang pengkarya, apakah itu sutradara, komposer, koreografer, atau perupa. Hal itu bahkan terlihat begitu kuat dalam kancah kajian kesenian, apakah itu menyangkut aspek filosofis, teologis, budaya, apalagi estetika.
Estetika yang akan kita lihat dalam seni pertunjukan kali ini adalah estetika dalam kaca mata Imannuel Kant, seorang tokoh filosof besar pada abad ke-18-19 (1724-1804). Kant bahkan menjadi salah satu pemikir yang paling berpengaruh bahkan hingga di era modern. Pengaruh pemikirannya terhadap kritik atas akal budi dan rasio murni, khususnya kritiknya atas estetika, menggoda saya untuk mencoba meimplementasikannya ke dalam pembacaan atas pertunjukan seni teater.
 |
Immanuel Kant (1724-1804),
Seorang Filsuf berkebangsaan Jerman
(Sumber Foto:www.philosophers.co.uk) |
Ada empat hal yang harus kita perhatikan dalam memandang estetika menurut Kant, yaitu: (1) bersifat universal; (2) tanpa pamrih; (3) tujuan tanpa tujuan; dan (4) keharusan (mutlak). Dari keempat butir pandangan estetika Imannuel Kant itu, saya mencoba membaca seni pertunjukan teater dengan lebih luas dan seksama, guna membantu merumuskan bagaimana pandangan kita terhadap seni teater, dalam kaitannya dengan unsur-unsur estetika.
Seni teater sejak awalnya memang bergerak bersama dan tak dapat dilepaskan dari suatu pandangan yang terkait dengan kepercayaan, keyakinan dan kebudayaan tertentu. Hingga pada akhirnya, dunia dan zaman yang terus bergerak mengubah banyak hal, bahkan permukaan ilmu pengetahuan. Seni teater, terus bergelut dengan dunia sastra, sosial, budaya, filsafat, teologis, dan berbagai hal lain di sekitarnya.
Sikap multidisipliner ilmu ini menyuguhkan nilai atau butir utama pandangan manusia terhadap seni teater, yaitu terutama pada sifatnya yang menguniversal. Sifat yang menguniversal inilah yang menambah nuansa dan citarasa yang lebih estetik ketika dipertunjukan. Salah satu contoh, ialah apa yang dapat dilihat pada pertunjukan seni teater, yang berangkat dari naskah lakon Menunggu Godot (Waiting For Godot).
Naskah yang ditulis oleh Samuel Beckett, yang berkebangsaan Irlandia ini, menawarkan suatu posisi, situasi dan kondisi manusia pada masa-masa pra dan pasca Perang Dunia pertama dan kedua, atau yang lebih dikenal dengan PD I dan PD II. Naskah Menunggu Godot kemudian mampu menyedot seluruh perhatian dunia. Ilustrasi utama naskah Menunggu Godot ini ialah tentang tokoh Vladimir dan Estragon menunggu Tuan Godot, yang tak kunjung datang. Anehnya, mereka sendiri tidak mengetahui, siapakah sebenarnya Tuan Godot, apa tujuannya, apa maunya.
Meski begitu, mereka berdua tetap bertahan menunggu Godot, dan senantiasa selalu menunggu. Selama menunggu, mereka berdua terus bermain, mempermainkan dan menipu diri mereka seolah-olah hidup dengan penantian yang panjang itu sangat berarti, meski yang pada akhir dan awal kisah, mereka mengucapkan dialog yang sama: “Tidak ada yang berguna’ (Nothing To Be Done)
Hal yang terjadi pada Vladimir dan Estragon seperti gambaran manusia pada umumnya, yang setelah kian lama hidup dalam penantian, dengan perang, konflik sedemikian rupa, dan seperti tengah menanti dan menunggu. Entah apa yang manusia tunggu, apakah ‘Tuhan’, atau ‘Kematian’?
Pemikiran yang serupa Vladimir dan Estragon pun pasti akan terpikirkan dan terpintas oleh setiap manusia, dengan bertanya: apakah tujuanku hidup, siapakah diriku, dan siapakah Tuhan yang sesungguhnya, atau apakah aku hanya menunggu kematian? Pertanyaan itu semua berkemungkinan pernah terlontar dan terpikirkan oleh setiap manusia, meski ada beberapa yang mencoba menegasikannya dan ada pula yang mencoba mengkajinya lebih dalam, entah itu melalui filsafat eksistensi, atau teologi.
Gambaran yang disebut oleh Kant sebagai ‘bersifat menguniversal,’ dari gambaran naskah lakon Menunggu Godot, melalui perwakilan tokoh Vladimir dan Estragon, dengan demikian, memiliki artian dan makna yang sangat berarti bagi setiap manusia dalam dunia ini. Tentunya untuk dapat kita renungkan dengan saksama, baik itu yang bersifat eksistensi kedirian, eksistensi dunia dan tuhan, atau pandangan filosofis kita masing-masing.
Pengalaman empirik yang secara tidak frontal ditujukan kepada seluruh manusia, ditransformasi ke dalam naskah lakon Menunggu Godot oleh Samuel Beckett. Tentunya, hal itu dapat menggangu benak dan pikiran kita, bahkan dapat mengubah banyak hal, ketika kita membaca atau menonton pertunjukan teater dengan naskah lakon Menunggu Godot karya Samuel Beckett ini. Di sinilah letak nilai estetika dari pertunjukan seni teater, khususnya berdasarkan pemikiran Imannuel Kant menurut pengamatan dan perenungan saya.
Selanjutnya, berdasarkan butir kedua estetika dari Kant, kita dapat mencoba melihat nilai estetika yang tanpa pamrih. Kembali kepada contoh pertunjukan teater (drama) Menunggu Godot karya Samuel Beckett. Kita ambil secara acak saja, entah siapa yang menyutradarai, atau memerankan, atau yang membuat tafsir dan kertas kerja dramaturgialnya.
Secara eksplisit, lakon Menunggu Godot, berbicara perihal absurditas yang sama, yakni sisi absurd dari kehidupan manusia. Ketika pertunjukan ini berlangsung, tentunya tidak sedikit penonton yang mengapresiasi atas pertunjukan Menunggu Godot. Secara general, mereka semua (audience), ingin mendapat nilai apresiasi baru dengan menonton pertunjukan.
Inilah yang menurut saya dimaksud dengan kriteria ‘tanpa pamrih’ dalam estetika Kant ini, yakni nilai inheren dalam karya seni pertunjukan, yang harus tidak dan tanpa tujuan sama sekali, kecuali memberi ruang penyadaran terhadap penonton, atau pemurnian diri (katarsis). Penyelenggaraan dari pertunjukan Menunggu Godot, merupakan sebuah tujuan yang murni tanpa adanya embel-embel kepamrihan.
Pementasan teater harus memiliki kemurnian, tanpa terkait dengan eksploitasi kepada manusia atau masyarakat. Karena ketika suatu karya seni diciptakan, katakanlah seni pertunjukan, maka suatu karya itu tidak memiliki nilai estetika dalam karyanya, yang ada hanya sebatas guna, yakni guna ekonomi, guna eksistensi, guna makna paradoks.
Saya percaya, bahwa ketika Samuel Beckett membuat naskah Menunggu Godot, yang dikerjakannya lebih kurang selama dua tahun ini, ia melihat berbagai peristiwa tragis di sekitarnya, yang bahkan karena terlalu tragisnya, kemudian malah muncul suatu ironi dan komik (komedi) dalam Menunggu Godot. Hal ini tentu saja sesuai dengan argumennya mengenai peristiwa yang ia tuangkan ke dalam naskah Menunggu Godot, yaitu, ‘lelucon adalah sumber penderitaan,’ (bukannya malah kebahagiaan) sebagaimana juga disinggung oleh Bakdi Soemanto dalam bukunya Menunggu Godot: Sebagai Studi Banding, Di Amerika Dan Indonesia.
Kiranya cukup jelas, bahwa sebagai sebuah lakon maupun pertunjukan teater, Menunggu Godot merupakan suatu karya seni yang memiliki nilai estetika sebagaimana yang diformulasikan dan dirumuskan oleh Kant, yakni estetika yang tanpa pamrih. Tentunya, kita boleh meyakini, bahwa masih banyak kesenian di luar sana, selain Menunggu Godot, yang sesuai dan sepadan dengan apa yang dipikirkan oleh Imannuel Kant sebagai kriteria ‘tanpa pamrih’ ini.
Butir ketiga dari pembahasan estetika Kant dia formulasikan sebagai ‘tujuan tanpa tujuan.’ Kesenian, sering diibaratkan dengan beribadah, di mana nilai murni untuk mencipta, berkarya, itu bukan merupakan suatu tujuan yang krusial untuk badani atau dunia saja, tetapi lebih dari pandangan keduniaan (imanen). Sama halnya dengan Kant ketika merumuskan pandangannya terhadap estetika dalam karya seni sebagai beribadah.
Setiap manusia memiliki suatu kepercayaan dan keyakinannya terhadap Tuhan, agama, atau jiwanya. Atas dasar itu, setiap umat manusia dengan akal budi murninya akan beribadah kepada yang kuasa, tanpa mengharapkan sesuatu hal. Hal inilah ditransformasikan oleh Kant ke dalam pandangannya terhadap estetika.
Kunci ini pulalah kiranya yang akan membawa kita untuk memandang bagaimana pertunjukan seni teater, misalnya kembali ke contoh pertunjukan Menunggu Godot. Misalkan, kita ambil ketika saya menyaksikan, pertunjukan seni teater dengan naskah lakon Menunggu Godot, anggap saja yang disutradarai oleh Afrizal Harun (salah satu dosen ISI Padangpanjang), yang menyutradarai pemeran Rico Melta Pratama dan kawan-kawan, dalam rangka tugas akhir minat pemeranan (Rico Melta Pratama).
Ketika pertunjukan ini berlangsung, saya duduk di bangku penonton, gedung Teater Arena Mursal Esten, ISI Padangpanjang. Saya akan menatap fokus ke depan, memerhatikan bagaimana pertunjukan berlangsung, mulai mengamati dari bentuk penggarapan, tematik, artistik yang dibangun, hingga ke permainan para aktor di atas panggung.
Ketika saya menyaksikan dengan seksama, dari skenario yang telah dibangun secara artifisial, saya mendapati suatu titik sentuh dengan kisah pertunjukan, titik yang begitu dalam bagi saya sendiri. Nilai murni, yang ditawarkan ke dalam pertunjukan dengan naskah lakon Menunggu Godot, memang seperti sudah ada keindahaan atau estetika yang inheren dalam dirinya (objek tunggal) dan seperti tidak memerlukan suatu elemen lain untuk menambah kualitas pertunjukan guna mencapai nilai estetis.
Estetika yang sudah terdapat dalam objek (inheren) ini, maksudnya, ialah adanya suatu kualitas dari penampakan dan realitas panngung ketika dilihat oleh pandangan manusia (audiens). Karena itulah, bisa dikatakan bahwa pertunjukan seni teater, yang salah satu studi kasusnya adalah naskah lakon Menunggu Godot, memanglah seni yang murni tanpa suatu penimbangan, apakah ini dapat dikatakan seni atau hanya sejenis kegiatan artifisial manusia, atau hanya sebatas buah tangan manusia.
Nilai Kemurnian (tanpa pamrih), yang tujuan tanpa tujuan dan sifatnya meng-univesal telah terbukti adanya bagaimana pertunjukan seni teater adalah merupakan suatu seni yang ideal bagi Kant, sementara itu, ada satu point dan nilai lagi yang harus diuji dalam pertunjukan seni teater dan sekali lagi, study kasusnya melalui pertunjukan dan naskah lakon Menunggu Godot, karya Samuel Beckett. Point terakhir adalah keharusan atau mutlak dan dengan mencoba melihat seni teater ideal bagi Kant dalam pandangannya dan rumusannya tentang estetika.
Saya memandang ini dengan keharusan, bahwa terhadap objek yang saya yakini ada suatu nilai estetis di dalamnya. Saya akan mencoba mencari alegori lain selain pertunjukan dan saya mencoba menkoherensikannya dengan pertunjukan seni teater. Ketika saya melihat suatu pemandangan, entah itu gunung, danau, perubahan iklim, benda seni, atau segala isi alam kosmik ini, saya tidak perlu memerhatikan secara panjang dan jlimet, untuk menyatakan bahwa di situ ada nilai estetisnya. Melainkan, saya mengharuskan sublim antara jiwa saya dengan apa yang saya pandang, amati, lihat, apapun itu bentuknya.
Keharusan benda (objek) yang sudah ada pada dirinya, suatu penampakan yang realitasnya ada atau tidak ada dalam benak pemikiran saya, yang mampu membuat saya sublim. Dengan kata lain, penyatuan (transformasi emosi) antara jiwa diri saya dan objek fenomena atau nomena, itulah yang disebut keharusan (mutlak) estetis dalam objek.
Dari gambaran atau alegori di atas, kita bisa pula mencoba menariknya ke dalam pertunjukan seni teater. Sama halnya dengan deskripsi singkat mengenai objek yang memiliki nilai estetis yang terdapat di dalamnya, pertunjukan seni teater, misalnya yangberangkat dari naskah lakon Menunggu Godot juga demikian.
Pada saat saya menyaksikan pertunjukan Menunggu Godot, saya langsung merasa sublim dan juga terkatarsiskan oleh berbagai nilai estetis yang ada pada naskah itu. Nilai-nilai terdapat pada berbagai aspek, mulai dari konflik yang ditawarkan, nilai moral, problematisasi yang dibawa dari setiap tokoh, maupun basis makna kontekstualnya terhadap perang dunia.
Dengan demikian, melalui cara menonton Menunggu Godot dengan kacamata Estetika Immanuel Kant ini, saya cenderung memandang seni teater, adalah suatu seni yang ideal dan layak untuk disaksikan oleh manusia (audiens). Spekulasi ini, juga merupakan pembuktian yang berdasarkan perumusan dan formulasi yang telah menjadi pemikiran Kant, sebagai seorang filosof, dan pengkritik akal budi dan rasio, bahwa untuk memandang estetika kita harus berdasarkan akal budi dan rasio, baik itu antara subjek dengan objek, atau manusia dengan benda yang diamati, dalam realitas dan tampakan.
oleh teraseni | Jul 28, 2016 | Uncategorized
Rabu, 27 Juli 2016 | teraSeni ~
 |
Pertunjukan Teater “Kekwa! Alami
Mimpimu,”
Produksi Piamare Creative Company, Yogyakarta
Dipentaskan 27-29 Desember 2015
(sumber foto: www.nationalgeographic.co.id) |
Banyak orang di negara maju senang bekerja dengan anak-anak, dan hal itu mendorong mereka untuk, salah satunya, menerjuni bidang seni teater anak sebagai pekerjaan. Banyak di antaranya yang berpendapat bahwa kegiatan berlatih dan bermain teater bersama anak justru mengajarkan mereka begitu banyak hal, yang tidak mereka peroleh dalam pergaulan mereka dengan orang dewasa.
Cathlyn Melvin, seorang sarjana Seni Teater di Amerika Serikat, mengakui bahwa dari semua kegiatan yang diikutinya sepanjang hidup, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, sekolah menengah, hingga lulus kuliah, ia memperoleh banyak pelajaran yang kemudian menjadi bahan untuk membangun jati diri dan dunianya. Tapi ketika ia menatap kembali seluruh kesibukan itu, ia menyadari bahwa dari semua yang ia ikuti, seni teaterlah yang paling memberinya pelajaran penting tentang siapa dirinya, dan sosok seperti apa yang ia inginkan untuk dicapai.
Tapi mengapa anak-anak sebaiknya berlatih dan bermain seni teater? Cathlyn Melvin, yang meraih gelar sarjana (BA) dalam bidang Seni Teater dari University of Wisconsin, AS, dan kini mengajar teater untuk siswa-siswa sekolah menengah atas kemudian mengatakan bahwa setidaknya ada lima alasan, mengapa anak-anak sebaiknya belajar teater, yakni:
Pertama, Teater memberi kesempatan untuk “berjalan dengan sepatu orang lain”
Selama bermain dan berlatih teater, anak-anak seperti berjalan berpuluh-puluh kilometer dengan sepatu orang lain. Artinya, ketika seorang anak berusaha membaca dan memahami karakter yang akan ia perankan, ia akan didorong untuk memikirkan tentang orang atau karakter itu. Mengapa orang itu berfikir dan bertindak demikian, atau membuat pilihan-pilihan tertentu? Apa yang berusaha dia dapatkan dari orang lain yang dia ajak bicara? Bagaimana cara ia bicara? Dengan sikap tubuh seperti apa dia bicara?
Intinya, sang anak belajar memahami orang lain, yakni tokoh yang diperankannya, serta tokoh-tokoh lain yang berinteraksi dengan tokoh yang diperankannya itu. Selain belajar tentang komunikasi, pelatihan teater serupa itu mengajarkan pula tentang empati. Sementara, banyak di antara kita sudah cukup maklum bahwa kemampuan komunikasi serta empati adalah salah dua keterampilan kepribadian utama yang diperlukan untuk menjadi pemimpin, di mana pun kelak sang anak bekerja, apakah menjadi pimpinan sebuah perusahaan, atau sebuah kantor pemerintahan, bahkan di keluarganya sendiri.
Empati dan komunikasi yang diajarkan melalui pelatihan teater bahkan juga akan berperan penting manakala di kemudian hari sang anak menjadi dokter atau guru, atau penyuluh pertanian. Melalui empati dan cara berkomunikasi yang baiklah, ia bisa mengerti penderitaan pasiennya, persoalan yang dimiliki muridnya, serta masalah-masalah yang dihadapi oleh para petani yang dibinanya.
Banyak yang mengatakan bahwa persoalan dunia hari ini adalah mengeringnya rasa empati dalam masyarakat. Orang tidak terbiasa lagi untuk meletakkan dirinya pada posisi orang lain, untuk dapat memahami keadaan dan kesusahan orang lain. Pelatihan seni teater akan mengajarkan anak-anak untuk saling mengerti satu sama lain di dalam grup latihan. Tapi seni teater mengajak anak-anak tanpa memaksa untuk berempati. Teater bersifat mencetuskan, mendorong, dan menginspirasi. Praktek latihan berkomunikasi dan berempati serupa ini tentunya akan menjadi dasar yang kuat bagi berkembangnya rasa persaudaraan dan kemanusiaan mereka.
Kedua, Teater tidak mendiktekan apa yang harus dirasakan
Seni teater berdasar dari dan berorientasi pada pengalaman pribadi. Memainkan peran, merancang set untuk berpentas, melihat latihan orang lain, memahami cara kerja suatu pementasan, akan memberi anak-anak perspektif, suatu sudut pandang bagi diri mereka sendiri. Namun apa yang dilihat oleh anak yang satu dari suatu peristiwa pentas, belum tentu sama dengan anak yang lain. Demikian pula perasaan dan dorongan yang diperoleh dari pementasan, tidak selalu sama.
Namun justru di untuk itulah seni teater dimaksudkan untuk anak-anak, yakni membuka ruang untuk semua peserta latihan untuk mengeksplorasi emosi dan pandangan mereka sendiri. Melibatkan anak-anak dalam seni teater membuat mereka belajar untuk bebas berpikir, bebas untuk merasa, dan bebas untuk menjelajahi siapa diri mereka sendiri, serta bebas untuk membayangkan ingin menjadi seperti apa mereka kelak.
Ketiga, Seni teater adalah media yang sangat bagus untuk memahami sastra dan sejarah
Ketika seorang anak belajar dalam suatu kelas seni teater, ia akan berkenalan dengan sebuah cerita, dengan sebuah naskah drama. Dari situ ia akan memperoleh pengetahuan awal tentang sastra. Ia juga akan belajar tentang bagaimana sebuah drama disusun, dalam bentuk alur cerita, pertikaian, penokohan, latar kejadian serta pesan cerita.
Tidak mustahil, perkenalan dengan naskah drama itu akan membawanya mengenali berbagai jenis karya sastra yang lain, misalnya puisi, prosa, cerpen atau novel. Dia juga akan mengetahui apa yang membedakan sebuah naskah drama dengan jenis karya sastra yang lain. Mereka juga akan berkenalan dengan nama-nama penulis karya sastra.
Drama yang paling digemari anak-anak adalah yang bernuansa petualangan dan kisah-kisah perjuangan. Mereka bisa belajar tentang sejarah dari naskah-naskah serupa itu. Tapi bukan untuk menghapal tanggal dan tahun kejadian, melainkan memahami situasi dalam kisah sejarah. Ini kelebihan teater sebagai seni peristiwa, di masa sejarah bukan sekadar dibaca, tetapi bisa dialami. Singkatnya, seni teater adalah media dan cara yang sangat bagus untuk memperkenalkan anak-anak dengan tema-tema sastra dan sejarah.
Keempat, teater adalah obat penawar bagi jiwa, pikiran, dan perasaan
Sederhananya, teater adalah terapi. Sebuah penelitian yang mengungkapkan “10 Strategi Penyembuhan Stress pada Anak-Anak” menyebutkan enam di antara cara yang jitu untuk mengurangi stress pada anak adalah: (1) bernyanyi; (2) bermain; (3) berimajinasi; (4) berekspresi; (5) bekerja dalam tim; dan (6) membayangkan masa depan. Dan hebatnya, teater memberi ruang sekaligus memberi pemicu bagi keenam strategi itu.
Kelima, Teater memberikan ruang bagi ketidaksempurnaan
Melalui pelatihan teater, anak-anak mendapat kesempatan untuk menjadi hal-hal yang mustahil, menjadi sebesar raksasa, sekeras batu, atau sekonyol badut. Teater mengajarkan ruang yang tak terhingga dan tak terduga. Teater adalah dunia bercerita, bermain dan bersenang-senang. Melalui pelatihan teater, anak-anak didorong untuk mencoba hal-hal baru. Mereka diajarkan untuk tidak takut mencoba, tanpa takut salah. Mereka akan dibuat memahami bahwa dalam hidup mencoba dan gagal itu bernilai satu, mencoba dan berhasil itu nilainya dua, sementara tidak mencoba nilainya nol.
Teater mengajarkan anak-anak bahwa tidak ada jawaban yang benar dalam seni, yang berarti mereka dapat menjelajahi, menghubungkan ide-ide baru, dan belajar dari apa yang mereka rasakan. Semuanya dapat dicoba sementara keberhasilan dan kegagalan dalam percobaan itu tidak memiliki konsekuensi negatif. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk melihat dunia kemungkinan yang tidak mereka peroleh dalam matematika atau sejarah.
Joe Breault, seorang Kepala Sekolah di sebuah sekolah di California, AS, mengatakan bahwa program seni teater membuat anak-anak menjadi lebih baik di pelajaran yang lain. Ya, teater membantu anak-anak menjadi seorang yang bersikap baik, berkarakter kuat, pemikir yang logis dan kritis, serta peka pada sesama dan lingkungannya.
Singkat cerita, melalui teater warga dunia yang lebih baik dapat dipersiapkan, dan bukankah itu tujuan utama pendidikan? Bukan mustahil, melalui teater anak, manusia bisa mengubah wajah dunia di masa depan. Karena melalui seni teater, anak-anak diajarkan untuk lebih berani, lebih kreatif dan lebih bertanggung jawab. Singkatnya, pelatihan seni teater akan meletakkan dasar yang kuat untuk berlatih berpikir kritis sekaligus berempati bagi anak-anak.
Lalu pertanyaannya, apakah sebaiknya anak-anak di Indonesia juga belajar sambil bermain melalui seni teater?
oleh teraseni | Jul 27, 2016 | Uncategorized
Rabu, 27 Juli 2016 | teraSeni ~
 |
Marcel Marceau, seorang aktor pantomim
asal Prancis, yang merupakan salah seorang
pantomimer paling terkenal abad 20
(Sumber: https://www.tz.de) |
Belakangan ini, pantomim semakin digemari anak muda dan anak-anak sekolah di negeri ini. Apalagi, karena kini semakin banyak saja kompetisi pantomim untuk berbagai kelompok usia, baik yang diselenggarakan oleh dinas dan kementrian pendidikan, maupun swasta. Namun bagaimanakah pantomim bisa menjadi bentuk tontonan populer seperti sekarang ini? Apakah yang demikian menarik hati dari bentuk tontonan yang mencampurkan antara kisah, tari, lelucon dan musik ini?
Kisah pantomim semula adalah kisah tentang petarungan antara yang baik melawan yang jahat, di mana terdapat harapan kemenangan bagi yang benar, setelah berbagai kesulitan dan bahaya yang dilaluinya. Kisah-kisah ini berakar dalam cerita Yunani kuno, yang kemudian berlanjut ke gedung-gedung pertunjukan Romawi, hingga akhirnya berkembang di Italia, Perancis, dan akhirnya di Inggris.
Cikal bakal pantomim konon sudah ada di Yunani Kuno sejak tahun 600 SM, di mana terdapat aktor yang menampilkan adegan konyol atau komikal dengan hanya menggunakan gerak tubuh saja. Di masa Romawi Klasik terdapat pula pertunjukan yang hanya disampaikan melalui tari dan lagu. Bentuk awal pantomim ini dinamakan phlyake, yakni pertunjukan peran jenaka yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari. Para pemeran dalam pertunjukan ini umumnya mengenakan kostum yang ganjil dan menarik perhatian serta mengenakan topeng.
Singkat cerita, pantomim adalah bentuk pertama sekaligus ajaib dari seni teater. Pantomim seperti yang kita kenal sekarang pertama kali berkembang di Inggris. Namun dasar bentuknya bermula dari sebuah tradisi teater yang mengandalkan improvisasi yang berkembang di Italia, bernama Commedia dell’Arte. Commedia dell’Arte adalah bentuk pementasan yang digelar di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Secara bentuk, Commedia adalah bentuk seni yang sederhana, serbaguna, dan populer, di mana para aktor mengenakan topeng yang membuat penonton dengan mudah bisa segera mengenali karakter yang dimainkan, yang memungkinkan aktor untuk membuat lelucon tanpa takut malu.
Perjalanan dari satu tempat ke tempat lain mengantarkan Commedia ke seluruh Eropa, sehingga dramawan seperti Shakespeare (Inggris) dan Moliere (Prancis) kemudian tertarik pada karakter dan tradisi Commedia. Peran kunci yang selalu ada dalam Commedia biasanya adalah: (1) orang tua (vecchi) pemuda (inamorati), dan pelayan (zanni).
Orang tua (vecchi) biasanya digambarkan sebagai seorang dokter yang menjual obat palsu, sarjana yang pengecut, seorang tua yang sia-sia mengejar wanita yang lebih muda, atau seorang Kapten yang sombong dengan catatan perang palsu. Sementara itu, pemuda biasanya adalah kekasih seorang gadis yang oleh orang tuanya dipaksa menikah dengan seorang pria tua kaya. Dalam banyak cerita commedia, biasanya pelayan bisa lebih pintar dan mampu memperdaya tuan mereka. Pesannya sederhana, bahwa orang kecil belum tentu juga lebih bodoh dari orang-orang besar.
Dari Commedia, pantomim lalu berkembang di Inggris. Seorang pria bernama John Rich, memainkan peran kunci dalam munculnya pantomim. John Rich adalah seorang penari, pemain akrobat dan sekaligus seniman mime. Di sekitar tahun 1720-an ia mengelola sebuah gedung teater di Lincoln Inn Fields. Di sanalah ia menciptakan sejenis hiburan baru dengan menampilkan petualangan Harlequin dan Columbine, para tokoh pelayan dalam Commedia.
Tokoh Harlequin ini ternyata menyenangkan luar biasa bagi penonton. Pertunjukan John Rich berkembang menjadi tontonan spektakuler tapi juga mengundang kontroversi besar. Kritik pedas dialamatkan kepada John Rich, karena dianggap mengembangkan hiburan asing dan mengancam nama besar Shakespeare dan teater serius. Namun John Rich mendapatkan dukungan David Garrick, seorang manager teater pada masa itu, yang menyadari potensi komersial dari bentuk tontonan yang baru muncul ini. David Garrick-lah yang kemudian menciptakan konvensi pantomin yang bertahan sampai hari ini.
Memasuki akhir abad ke-18, muncullah badut modern melalui kreativitas Joseph Grimaldi, yang dianggap menjadi penemu berbagai lelucon pantomim paling terkenal, misalnya adegan tergelincir, lari ketakutan, dan lain-lain. Joseph Grimaldi menjadi badut modern karena menggambarkan tokoh-tokoh dari kehidupan perkotaan. Ia mengubah tradisi badut dengan mengenakan kostum baru, menggantikan badut yang biasanya tampil bodoh, dengan karakter berwajah putih dan pipi merah, bercelana longgar, dengan tubuh dan wajah yang elastis dan ekspresif. Kesan wajah pantomimer masakini, sebenarnya berasal dari gaya Joseph Grimaldi ini.
Joseph Grimaldi kemudian menjadi salah satu karakter paling terkenal di London pada masanya. Penonton sangat senang dengan kenakalannya dan mereka menontonnya tanpa henti justru karena ia menciptakan di atas panggung fantasi tentang sebuah dunia yang berbeda: sebuah dunia tanpa kelaparan, dunia balas dendam komik terhadap penguasa yang sangat menindas. Joseph Grimaldi menjadi salah satu satiris besar pada zamannya, seorang badut yang tidak saja menghibur tapi juga mampu memberikan komentar cerdas dan menggelikan terhadap perkembangan fashion, teknologi, transportasi, bahkan politik .
Pada akhir abad ke-19, wajah pantomim berubah. Seorang tokoh bernama Dan Leno menampilkan karakter baru, yang jauh dari gambaran badut sebelumnya. Ia menampilkan tokoh bintang tak terduga, yakni seorang ibu yang letih, lesu, sedikit bergosip, dan berjuang untuk mengatasi dunia yang mulai tidak ramah. Pantomim berubah arah ke sekitar kisah keluarga yang yang aneh. Dan Leno adalah pemain musik terkenal yang menciptakan karakter yang dinamakan “Dames” ini, yakni wanita kelas pekerja yang cerewet.
Tokoh “Dames” sebenarnya telah lama ada dalam tradisi pantomim, tapi mereka biasanya dipandang hanya sebagai karakter konyol. Hal inilah yang diubah oleh Dan Reno menjadi karakter-karakter utama. Pada tahun 1880-an, Leno mulai memainkan peran seperti Ratu atau Janda. Perlahan-lahan, ia mulai menciptakan “Dame” yaitu seorang ibu yang menghadapi masalah kemiskinan, pengangguran dan ditinggalkan.
Dan Leno, pria kecil kurus, dengan wajah sayu dan suara serak, dan dikatakan memiliki ‘mata paling menyedihkan di dunia’ memunculkan persoalan absurditas hidup dalam pantomim. Dan Leno mulai memberi kesadaran tentang berpadunya antara simpati dan tawa dalam pantomim. Ia memunculkan karakter perempuan yang hidup di dunia yang kacau balau dan penuh bencana. Dan Leno dengan tokoh-tokoh “Dame”-nya, bermain pantomim dengan irama yang menggugah, kadang berbicara obrolan ngawur seperti layaknya orang berbicara sehari-hari, tetapi pada saat yang sama, ia memberi pantomim plot dan tema-tema yang lebih dekat dengan budaya hidup sehari-hari, terutama dengan kenyataan hidup kelas pekerja.
Nah, bagaimanakah pantomim hari ini jika dibandingkan dengan tradisi pantomim yang dibangun John Rich, Joseph Grimaldi, dan Dan Reno itu?
oleh teraseni | Jul 25, 2016 | Uncategorized
Senin, 25 Juli 2016 | teraSeni ~
Tulisan berikut adalah review atas tulisan berjudul “Krisis Sinden”: Gender, Politik dan Memori Seni Pertunjukan, dari Andrew N. Weintraub, yang memiliki judul asli “The “Crisis of the Sinden”: Gender, Politics, and Memory in the Performing Arts of West Java,1959-1964,” yang dimuat dalam: Indonesia, No. 77 (Apr., 2004), pp. 57-78, dipublikasikan oleh : Southeast Asia Program Publications at Cornell University.
Andrew Weintraub membuka artikelnya dengan mengutip sebuah laporan dari tahun 1966, atau di awal Orde Baru, yang menggambarkan secara hiperbola bagaimana sinden di sekitar tahun 1950-an dapat demikian ‘menyihir’ masyarakat. Sinden adalah penyanyi perempuan tradisional, yang pada awalnya tergabung dalam
tradisi seni pertunjukan Wayang Golek di Jawa Barat, yang kemudian berdiri sendiri sebagai sebuah profesi. Menurut Weintraub, laporan itu menarik karena memotret posisi sinden sebagai: (1) pusat perhatian massa penonton; dan (2) sekaligus sebagai sumber kekacauan social, kejahatan bahkan pembunuhan.
 |
Sebuah Kompetisi Bertajuk Sinden Idol
(Sumber Foto:www.berita.suaramerdeka.com) |
Masa-masa tahun 1950an akhir, oleh K.S. Kostaman, seorang penulis sekaligus pemerhati (aficionado) Wayang dinamakan masa “krisis sinden.” Di masa-masa ini, poplularitas sinden bahkan dapat melampaui dalang, orang yang seharusnya menjadi tokoh sentral dalam sebuah rombongan wayang. Menariknya, masa-masa yang ditunjuk sebenarnya sejajar dengan masa-masa “Demokrasi Terpimpin” Presiden Soekarno, yakni antara tahun 1959-1965, yang umumnya dalam sejarah Indonesia digambarkan dengan ciri: (1) menguatnya Negara; (2) kesulitan ekonomi; dan (3) menguatnya faksionalisasi politik.
Kemunculan “krisis sinden” ini dimulai ketika para sinden memupuk popularitas dengan dua cara, yakni: selain dengan menyanyikan lagu-lagu baru yang popular, juga dengan menggoyangkan tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang di masa itu dianggap ‘provokatif secara seksual.’ Kontroversi tentang sinden berlanjut, ditandai dengan sebuah simposium yang didukung pemerintah dan dikawal oleh tentara dan polisi pada tahun 1964. Simposium itu berusaha mendorong sebuah ‘kode etik’ bagi para sinden untuk mencegah mereka dari tarian, lagu yang interaktif, dan semua praktik yang bisa membuat pertunjukan mereka menjadi menggairahkan dan menyemangati penonton.
Berdasarkan fenomena itu, Andrew Weintraub dalam artikelnya berusaha menelusuri lebih jauh perihal: (1) bagaimana cara para sinden memperoleh keistimewaan dalam pertunjukan yang didominasi laki-laki; (2) mengapa Negara menjadi ikut campur dalam seni pertunjukan lokal?; dan (3) apakah landasan material dan kultural yang membuat krisis sinden menjadi berhubungan dengan krisis nasional pada waktu itu?
Weintraub berargumentasi bahwa tahun-tahun yang juga kerap disebut “jaman sinden” ini adalah masa di mana perubahan nomor music, gaya, estetika dan teknologi telah mengubah peran sinden dalam seni pertunjukan. Lebih jauh, ‘krisis sinden’ yang melibatkan kuasa Negara pada dasarnya adalah perjuangan untuk memperoleh otoritas kultural dari beberapa ideologi yang saling bersaing.
Sinden dalam Perspektif Sejarah
Penyanyi perempuan pertama yang tampil dalam tradisi wayang golek diperkirakan adalah Nyi Arwat, di akhir abad XIX, yang dibawa oleh dalang Bradjanata. Pada masa ini, seturut Kathy Foley, penyanyi perempuan yang disebut sebagai ronggeng sepenuhnya dikooptasi oleh dalang dan terkadang juga berprofesi sampingan sebagai wanita penghibur. Dengan cara itu, para dalang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan membangun model hubungan antara sinden-dalang. Pernikahan, dipakai sebagai cara mempertahankan kooptasi dan membentuk pola hubungan dalang/suami bersama sinden/istri-nya.
Memasuki tahun 1930-an, banyak sinden mulai terdengar di radio dan memperoleh popularitas yang lebih luas. Beberapa lagu mulai identik dengan sinden tertentu. Pada tahun 1942, nama sinden bahkan mulai terdengar dalam iklan, bersama nama dalang. Sinden lantas mulai muncul sebagai ‘bintang’ dan mematahkan dua pandangan umum, yakni: (1) yang berkaitan dengan kodrat wanita yang lemah, pasif dan menerima; serta (2) yang berkaitan dengan citra negatif sebagai ronggeng.
Selama tahun 1940an, terutama melalui kiprah seorang sinden bernama Arnesah, citra modern sinden mulai muncul, ditandai dengan munculnya nomor dan komposisi baru. Sinden bahkan mulai dipromosikan sebagai seorang ‘pembaharu’ yang memajukan kebudayaan Indonesia. Nama ronggeng lalu berubah menjadi ‘juru sinden.’. Pendekatan lain yang digunakan untuk memperbaiki citra sinden, terutama pada permulaan tahun 1950an ialah dengan menggunakan nama mereka sendiri sebagai nama panggung, meninggalkan kebiasaan lama, tahun 1930an, yang biasanya menggunakan nama samaran.
Pengaruh amplifikasi elektronik turut berperan dalam perubahan citra ini. Penonton pun kemudian mulai melakukan pembedaan atas sinden, yang sekaligus mewakili selera kelas sosial. Mereka misalnya membedakan antara Upit Samarinah yang suaranya untuk kelas atas, dengan Titim Fatimah yang cenderung untuk kelas menengah ke bawah. Pola hubungan antara sinden dan penonton pun berubah. Mereka tidak lagi berinteraksi dengan sinden dengan cara memasukkan uang di antara payudara para sinden seperti di masa lalu, melainkan kini dengan menulis surat pribadi.
Perubahan pola ini membuat sinden menjadi semakin penting posisinya bahkan mengancam kedudukan dalang dalam pertunjukan. Para sinden bahkan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Para penonton kemudian mulai lebih mengenal dan mengundang sebuah grup wayang golek karena sinden-nya ketimbang karena dalang. Posisi sebagai pembaharu dan pencipta lagu, membuat para sinden menjadi saluran bagi penonton untuk mencari keterlibatan dan perubahan dalam seni pertunjukan.
Demokrasi Terpimpin
Menyadari bahwa Negara yang masih muda memiliki kesulitan tertentu dalam menyatukan visi, ditambah dengan banyaknya partai politik dalam system demokrasi liberal, membuat Soekarno harus menguatkan kepemimpinannnya. Melalui dekrit presiden 1959, ia mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan mengajukan MANIPOL USDEK (Manifesto Politik/ Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dan NASAKOM (Nasional Agama Komunis) sebagai proyek nasional. Dengan mempersatukan empat kekuatan partai politik di Indonesia (PNI, Masyumi, NU, dan PKI), Soekarno bermaksud menandingi kekuatan angkatan bersenjata secara politik.
Namun dalam praktiknya kemudian Posisi Demokrasi Terpimpin-Soekarno lebih dekat dengan PKI, yang dalam beberapa hal ia pandang lebih mendukung cita-citanya, yakni revolusi Indonesia. Tapi pilihan politik ini kemudian membuktikan kegagalan Soekarno menjalankan system ’Negara modern,’ yang kemudian berakibat tingginya inflasi, kehancuran infrastruktur, dan menurunnya hasil pertanian. Pembunuhan enam jendral pada tanggal 1 Oktober 1965, kemudian memberi kesempatan kepada tentara untuk mengambil alih kekuasaan melalui Soharto, yang memerintah hingga tahun 1998.
Konferensi Wayang Golek 1964
Situasi selama tahun 1960-an di Indonesia membuat “krisis sinden” menjadi bagian dari krisis politik nasional. Secara regional, “krisis sinden” mendorong pemerintah daerah untuk kemudian mengintervensi persoalan kesenian. Pada tahun 1961 berdirilah Yayasan Pedalangan Jawa Barat yang bertujuan untuk menjembatani kembali antara dalang dan sinden. Organisasi ini lantas melaksanakan sebuah simposiun di tahun 1964 yang disponsori oleh Kantor Gubernur Jawa Barat, Pos Militer, Kepolisian Jawa Barat, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Simposium itu kemudian melahirkan buku Buku Pangeling-ngeling Seminar Padalangan (BPSP), yang pada dasarnya berisikan “tata tertib kebudayaan Indonesia.”
Hal yang paling disoroti adalah seni pertunjukan yang dianggap tidak sesuai atau tidak memiliki integritas, terutama para sinden yang bergoyang di hadapan penonton dan dapat membuat penonton menjadi ‘gila’. Simposium bahkan berfokus pada pengaturan gender dalam pertunjukan, yang intinya ingin membuat aturan bagi para sinden. Simposium kemudian menghasilkan ‘aturan’ yang terdiri dari: (1) sinden dan dalang harus duduk di sejajar sebagi musisi; (2) lagu berulang (sindir-sampir) akan dipersingkat; dan (3) semua lirik yang dipandang bersifat cabul akan diubah menjadi lirik yang bicara tentang pembangunan) dan identitas nasional Indonesia.
Forum kemudian juga menyepakati Sila Kahormatan Seniman-Seniwati yang dibuat atas: (a) mandat Koordinator Pertahanan dan Keamanan- Kepala Staf Angkatan bersejata, Jendral A. H. Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prijono; (b) saran pemerintah dan komandan militer daerah; serta (c) para dalang paling kesohor, di antaranya Elan Surawisastra, R. U. Partasuwanda, R. Gunawan Djajakusumah, Engkin Sukatmamuda, A. Sunarya, dan Somasondjaja Sukatmaputra. Sila Kahormatan Seniman-Seniwati ini, antara lain memuat:
… [kepada seniman]
3. Dalam principenja seniman/seniwati pedalangan sedjadjar harkat dan deradjatnja. Oleh karena itu pemanggungan harus diichtiarkan tempatnja jang sedjadjar pula.
4. Harus ada disiplin jang tertulis jang merupakan code ethiek (sila kehormatan) seniman/seniwati pedalangan. Oleh karena itu ditetapkan sila kehormatan terlampir.
5. Harus ada kesponanan dalam pemanggungan.
… [kepada pemerintah]
2. Melarang segala tjara pemanggungan jang dapat menimbulkan keonaran kesenian (merobah pertundjukkan wayang golek djadi djoged atau tjara2 pertundjukkan jang melanggar susila).
3. Inspeksi Kebudajaan, Front Nasional dan badan2 Pemerintah lainnja jang ada hubungannja supaja memberi bimbingan jang njata kepada seniman/seniwati Pedalangan.
… [kepada masarakat]
2. Masarakat diminta agar ikut mengawasi dan melindungi seni pedalangan dengan djalan mentjegah adanja pertundjukkan wajang golek jang dirobah mendjadi perdjogedan dan tjara2 pertundjukkan jang melanggar susila.
3. Masarakat jang mengadakan pertundjukkan wajang golek diminta agar memenuhi perdjandjian2 jang telah disetudjuinja sebelum pemanggungan antara jang meminta pemanggungan dan jang memberi pertundjukkan.
Berdasarkan semua hal itu, Andrew Weintraub memandang bahwa resolusi itu solah menganjurkan kesejajaran antara artis pria dan artis wanita, namun pada dasarnya bertujuan untuk membatasi ruang gerak para sinden dan mencegah mereka melampaui para dalang. Di sisi lain, melalui wacana ini, sinden diseret ke dalam pertarungan ideology, yakni dengan memanfaatkan kemampuan mereka dalam menarik massa. Sebagian sinden kemudian direkrut oleh PKI dan tampil dalam beberapa acara LEKRA. Sementara sebagian lainnya, dilindungi pemerintah daerah dan TNI.
Sinden dan Ingatan Budaya
Representasi Pemerintahan Orde Baru dan Pasca Orde Baru di Indonesia tentang sinden, melalui publikasi resmi pemerintah maupun media massa, kemudian menggambarkan bagaimana media membangkitkan ingatan budaya perihal masa-masa “krisis sinden.” Berbagai tulisan menggambarkan wayang golek dari masa yang dinamakan juga sebagai “jaman sinden” ini sebagai sesuatu yang liar, tidak terkendali, di mana kejahatan bahkan pembunuhan dapat timbul. Praktik sinden dikonstruksikan sebagai sebagai pertunjukan yang berbahaya bahkan berlawanan dengan ideologi Negara.
Wacana “krisis sinden” bahkan kemudian digunakan oleh Orde Baru sebagai bagian dari kampanye anti komunis. Masa-masa “jaman sinden” digunakan untuk menggambarkan kekacauan social selama pemerintahan Demokrasi Terpimpin-presiden Soekarno. Lebih jauh, digambarkan bahwa kebangkitan sinden di masa lalu adalah pertanda dari kekacauan 1965. Bahkan, diyakini: jika sinden kembali menguat, maka kekacauan, korupsi, dan melemahnya Negara akan kembali muncul.